Filosofi tentang Waktu di Antara Kehilangan dan Cinta
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar

Kehilangan datang sebagai penagihnya, sementara cinta hampir selalu datang sebagai janji. Waktu berdiri di antara keduanya, menentukan segalanya seperti hakim yang diam. Kita sering berpikir bahwa cinta adalah tentang perasaan, dan kehilangan adalah tentang nasib. Namun, jika kita melihat lebih dalam, keduanya adalah tentang waktu, tentang kapan kita bertemu, berapa lama kita bersama, dan kapan semuanya runtuh atau hanya menjadi kenangan.
Waktu sering dianggap sebagai komoditas dalam kehidupan modern yang serba cepat. Tenggat waktu, kalender, dan notifikasi digital digunakan untuk mengukurnya. Tetapi dalam hal cinta, waktu tidak pernah berhenti. Ia bisa berlanjut ketika pesan tidak datang dan menunggu kebahagiaan terasa terlalu singkat. Saat ini, filsafat waktu menemukan bahwa itu paling manusiawi. Bukan di kelas, tapi di hati orang-orang yang pernah dicintai dan kehilangan.
Dalam Confessiones, Agustinus bertanya dengan jujur dan berasumsi, “Apakah itu waktunya?” Jika tidak ada yang bertanya, saya mengetahuinya. Jika saya harus menjelaskan, saya tidak tahu. Jika seseorang mencoba menjelaskan rasa kehilangan, pernyataan ini mungkin terdengar familiar. Meskipun kita tahu untuk mempertahankan perasaan kita, kita tidak menggunakan bahasa yang cukup. Kehilangan selalu terasa seperti kehilangan waktu. Masa lalu terasa terlalu hidup, saat ini terasa tidak ada artinya, dan masa depan tampak tidak jelas.
Waktu berada di dalam kesadaran manusia, bukan di luar diri manusia, menurut perspektif Agustinus. Masa lalu dipersembahkan oleh kenangan, masa depan dipersembahkan oleh harapan, dan saat ini disajikan oleh perhatian. Dalam tiga lapis itu, cinta bertahan. Kami hidup karena kenangan, harapan, dan cinta. Tiga lapisan ini runtuh sekaligus saat kehilangan. Ingatannya berubah menjadi beban, harapan berubah menjadi ketakutan, dan saat ini terasa kosong.
Hingga tahun 2025, penelitian psikologi kognitif menemukan bahwa pengalaman emosional yang kuat, terutama cinta dan kesedihan, mengubah persepsi subjektif manusia tentang waktu. Studi lintas negara yang diterbitkan dalam Nature Human Behavior (2024–2025) menemukan bahwa orang yang mengalami kehilangan besar cenderung mengalami “time dilation”, yaitu perasaan bahwa waktu berjalan lebih lambat selama fase keringat. Sebaliknya, fase jatuh cinta awal sering menciptakan ilusi bahwa waktu berjalan lebih cepat. Data ini mendukung gagasan yang telah lama disampaikan para filsafat bahwa waktu adalah pengalaman dalaman dan bukan hanya kronologi.
Henri Bergson menyebut “durée”, waktu yang tidak dapat dikurangi menjadi detik, menit, atau tahun. Dalam cinta, durasi ini benar-benar terasa. Dua orang bisa bersama selama bertahun-tahun, tetapi itu membuatnya terasa hampa. Keakraban singkat seperti itu bisa bertahan seumur hidup. Menurut Bergson, kehilangan berarti tidak hanya berakhirnya suatu hubungan, tetapi juga berhentinya suatu jangka waktu. Oleh karena itu, perpisahan sering terasa tidak proporsional dengan durasi hubungan. Bukan jumlah waktu yang hilang, namun kualitas waktu yang hilang.
Di era media sosial, masalah tentang waktu yang tepat untuk berhubungan dan kehilangan seseorang menjadi semakin kompleks. Logaritma menggunakan logika keberadaan abadi. Masa lalu dapat ditolak sepenuhnya oleh jejak digital, foto lama dapat muncul kembali sebagai “kenangan”, dan pesan lama dapat dibaca ulang. Data dari Laporan Kesehatan Digital 2025 menunjukkan peningkatan gangguan pemulihan emosional setelah putusnya hubungan, terutama karena paparan memori digital. Arsiv yang terus hidup justru mempersingkat waktu penyembuhan.
Pada titik ini, Martin Heidegger tampaknya menjadi relevan. Menurut Being and Time, manusia adalah makhluk temporal. Meskipun kita berada dalam waktu, kita juga dibentuk olehnya. Menurut Heidegger, cinta adalah usaha eksistensial. Kami memilih seseorang untuk berkontribusi pada masa depan kita. Oleh karena itu, kehilangan bukan hanya kehilangan orang, tetapi juga runtuhnya kemungkinan yang pernah kita rencanakan. Oleh karena itu, kecemasan yang tidak selalu beralasan sering disertai dengan kehilangan. Kita tidak hanya membandingkan apa yang telah terjadi, namun juga membandingkan apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu yang sebelumnya terbuka tiba-tiba terasa tertutup. Menurut Heidegger, kita dihadapkan kembali pada kefanaan, kenyataan bahwa semua kemungkinan hanyalah sementara.
Namun, modernitas seringkali memberi kita pilihan yang salah. Cinta harus “cepat pasti”, sedangkan kehilangan harus “segera move on”. Semuanya terlihat efektif, termasuk perasaan. Sebaliknya, filsafat waktu mengajarkan tentang kesabaran eksistensial. Dengan gagasan kekambuhan abadi, Friedrich Nietzsche menantang orang untuk mencintai hidup mereka sehingga mereka bersedia kembali tanpa penyesalan. Pertanyaannya, “apakah kita sungguh-sungguh hadir dalam cinta, atau sekadar melewatinya sambil lalu?” menjadi tajam ketika dia berada di dunia cinta.
Cinta yang tidak memenuhi harapan sering mengakibatkan kehilangan yang berlarut-larut. Bukan karena perpisahannya, tapi karena penyesalan atas waktu yang tidak terpakai dengan baik. Nietzsche mengingatkan bahwa waktu tidak dapat diubah. Ia hanya dapat digunakan atau disia-siakan. Survei World Values Survey Wave 8 menarik perhatian bahwa selain kecenderungan untuk hubungan jangka pendek, ada peningkatan kekhawatiran tentang eksistensi setelah hubungan berakhir. Ini merupakan paradoks. Hubungan lebih singkat, tetapi penderitaan emosional lebih lama. Membaca paradoks ini lebih mudah dengan filosofi waktu. Kehilangan akan kehilangan konteksnya dan manusia kehilangan narasi untuk memulihkan diri ketika hubungan dianggap sebagai sebuah fragmen.
Konsep narasi waktu ditawarkan oleh Paul Ricoeur sebagai titik awal. Dia mengatakan bahwa manusia dapat memahami waktu melalui cerita. Kebersamaan adalah inti dari cinta, dan kehilangan adalah inti dari perubahan. Tidak hanya kehilangan dirinya sendiri yang berbahaya, namun juga kegagalan untuk menerapkannya. Waktu berhenti menjadi guru dan berubah menjadi penjara ketika kehilangan tidak dimaknai. “Waktu akan menyembuhkan” adalah ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sebagian darinya benar. Tidak ada perbaikan tanpa waktu. Ia hanya memberikan ruang; yang menyembuhkan adalah cara kita hidup di dalamnya. Apakah kita memaknai waktu sebagai proses menjadi, atau kita membiarkan waktu berlalu tanpa mempertimbangkannya?
Kehilangan dan cinta pada akhirnya bukanlah dua sisi yang sama sekali bercampur. Keduanya melambangkan dua sisi pengalaman manusia yang bersifat temporer. Karena kita tahu waktu kita terbatas, kita mencintai. Kami kehilangan waktu. Manusia belajar tentang dirinya sendiri di keduanya. Tidak ada nasehat yang diberikan oleh filsafat waktu tentang cara membuat kehilangan atau cinta yang abadi. Ia hanya memberi kita satu pelajaran penting: bahwa berdamai dengan waktu adalah kunci hidup. Dalam cinta kita belajar hadir, dalam kehilangan kita belajar melepaskan, dan dalam waktu kita belajar menjadi manusia seutuhnya, dengan segala kerapuhan dan harapan yang menyertainya.
Saya takut bahwa itu mungkin satu-satunya cara yang benar-benar menghibur. Bahwa waktu memang akan berlalu, namun artinya tidak akan pernah hilang. Ia tetap hidup, tersembunyi dalam kenangan, dalam cerita, dan dalam cara kita mencintai lagi dengan kesadaran bahwa setiap detik selalu berharga karena ia tidak akan kembali.
- Penulis: Riki Arista
- Editor: Redaktur Balengko



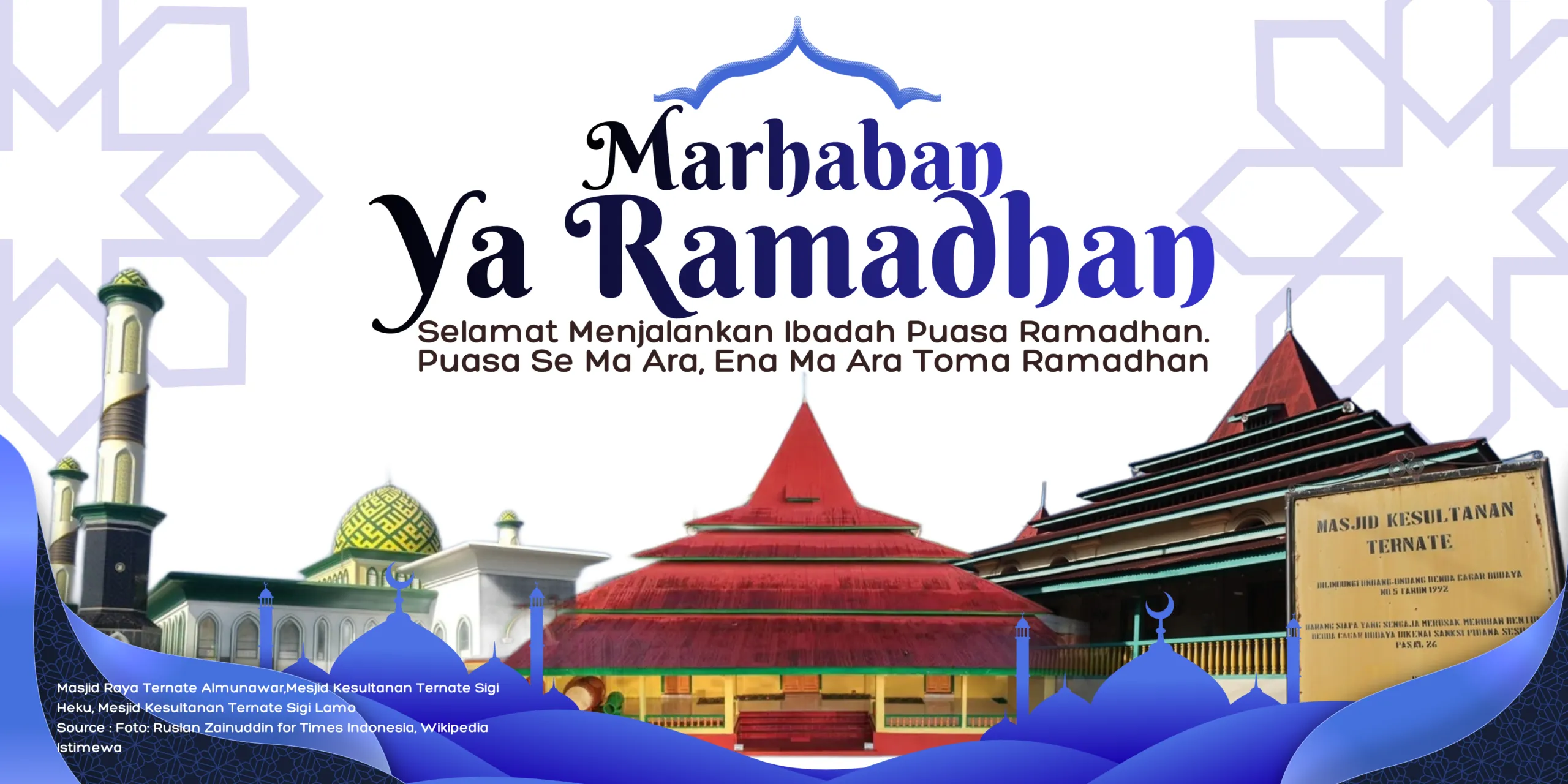
























Saat ini belum ada komentar