Dari Sajdah ke Kesadaran: Ramadan dan Tanggung Jawab Menjaga Bumi
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 97
- comment 0 komentar
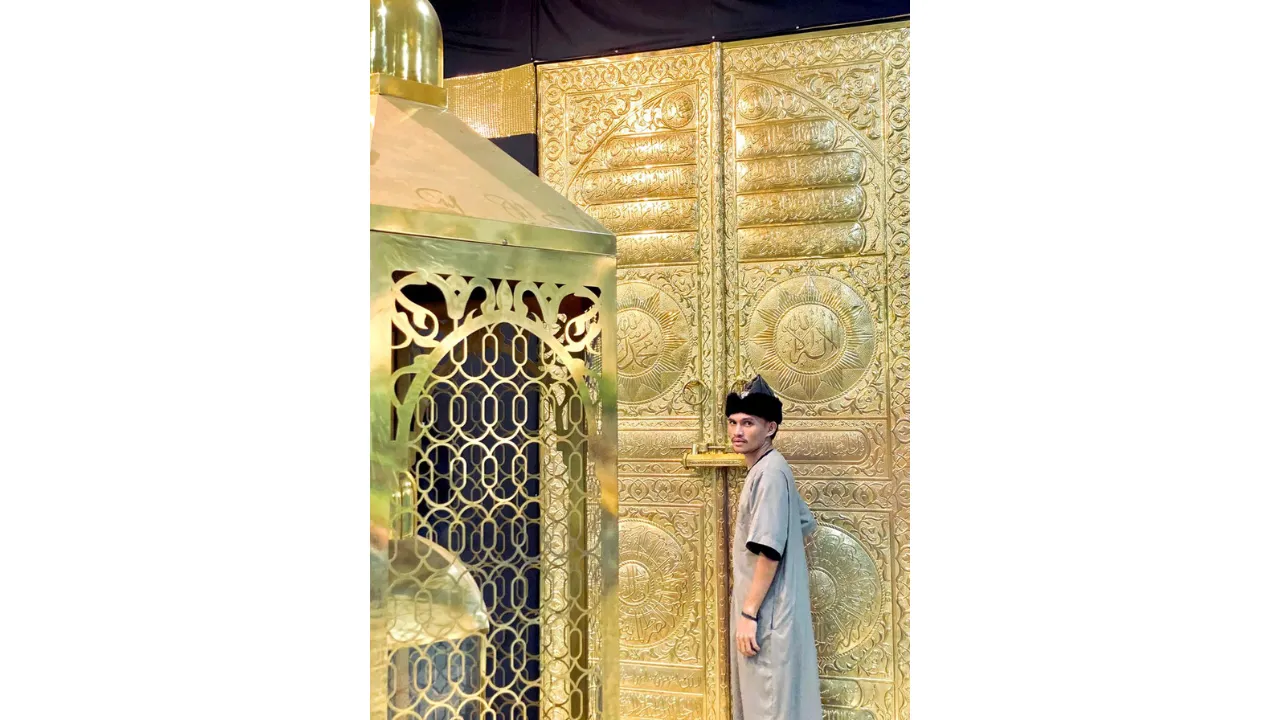
Source : Istimewa
Di awal bulan Ramadan ini, mari kita berhenti sejenak. Sebab di tengah ibadah yang kita jalani, ada ketertindasan yang terus berlangsung di hadapan mata dan batin kita.
Ramadan bukan sekadar menahan lapar, dahaga, dan nafsu. Ia seharusnya menjadi latihan empati—agar kita tidak lagi memandang penderitaan sebagai sesuatu yang biasa. Lebih dari itu, puasa adalah momentum kesetaraan. Di hadapan lapar dan dahaga, jabatan runtuh, kekayaan tak lagi berjarak. Pemegang saham, pemimpin negara, orang kaya, dan mereka yang terpinggirkan berdiri pada titik yang sama—rapuh, terbatas, dan sama-sama membutuhkan Tuhan.
Tuhan Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui membentangkan ampunan tanpa batas. Tetapi kita sering kali hanya mendekat ketika Ramadan tiba. Setelah ia pergi, kita kembali membangun jarak—antara kaya dan miskin, antara kuasa dan yang tak bersuara—seakan langit dan bumi memang ditakdirkan untuk tak pernah saling menopang.
Pada momen ini, Ramadan seharusnya menjadi cermin. Sebab selama sebelas bulan kita kerap mengaminkan kemewahan, sementara ketertindasan dan keterbelakangan berjalan tanpa gangguan.
Kita tahu itu. Kita melihatnya. Namun kita memilih terbiasa. Seakan semua terjadi tanpa sebab, padahal sebab itu tumbuh dari cara pandang kita sendiri—cara pandang yang membiarkan jarak antara kaya dan miskin semakin lebar.
Dari bulan suci ini pula kita seharusnya belajar bahwa rasa lapar yang kita rasakan sejak terbit matahari hingga terbenamnya bukanlah pengalaman musiman. Bagi sebagian orang, lapar adalah kenyataan setiap hari. Bukan hanya di bulan Ramadan.
Ada mereka yang kesulitan mendapatkan sesuap nasi dan sekeping uang. Ada pula yang kehilangan tanahnya—diambil, digusur, atau terpaksa dijual karena kerasnya kehidupan.
Maka pertanyaannya: apakah Ramadan hanya akan menjadi ritual tahunan, atau sungguh menjadi kesadaran yang mengubah cara kita memandang mereka yang hidup dalam lapar tak berkesudahan?
Memang, Ramadan sering kita pahami sebagai ritual yang menjanjikan pengampunan Tuhan. Namun jika maknanya berhenti pada urusan dosa pribadi, itu terlalu sempit.
Penghapusan dosa bukan sekadar janji langit, melainkan panggilan untuk mengubah cara kita memperlakukan bumi—dan manusia di dalamnya.
Di titik ini, Ramadan seharusnya melahirkan kesadaran kolektif. Bukan hanya tentang kesetaraan antarmanusia, tetapi juga tentang hubungan kita dengan alam.
Sebab, selama ini kita memperlakukan bumi seolah ia terpisah dari diri kita. Padahal kita tumbuh darinya, hidup darinya, dan akan kembali kepadanya.
Maka penyucian tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ia harus menjalar pada cara kita menjaga tanah, air, dan hutan—agar Ramadan tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga memulihkan bumi.
Cara pandang ini tidak hanya hidup di satu wilayah. Ia menjalar di banyak pulau yang tanahnya kaya, tetapi manusianya kerap terabaikan. Dan saya tidak perlu pergi jauh untuk melihatnya.
Saya melihatnya di Halmahera—tanah yang membesarkan saya. Di sana, relasi kuasa berdiri lebih tinggi dari suara rakyat. Ketidakadilan tidak lagi mengejutkan; ia telah menjadi kebiasaan.
Ramadan akan benar-benar terasa jika pertobatan kita meluas—bukan hanya dari dosa pribadi, tetapi juga dari luka yang kita sebabkan pada bumi. Larut dalam sujud untuk memohon ampun, lalu bangkit dengan kesadaran menjadi khalifah: penjaga, bukan perusak.
- Penulis: Gilang Hi Adam
- Editor: Redaktur Balengko Creative Media

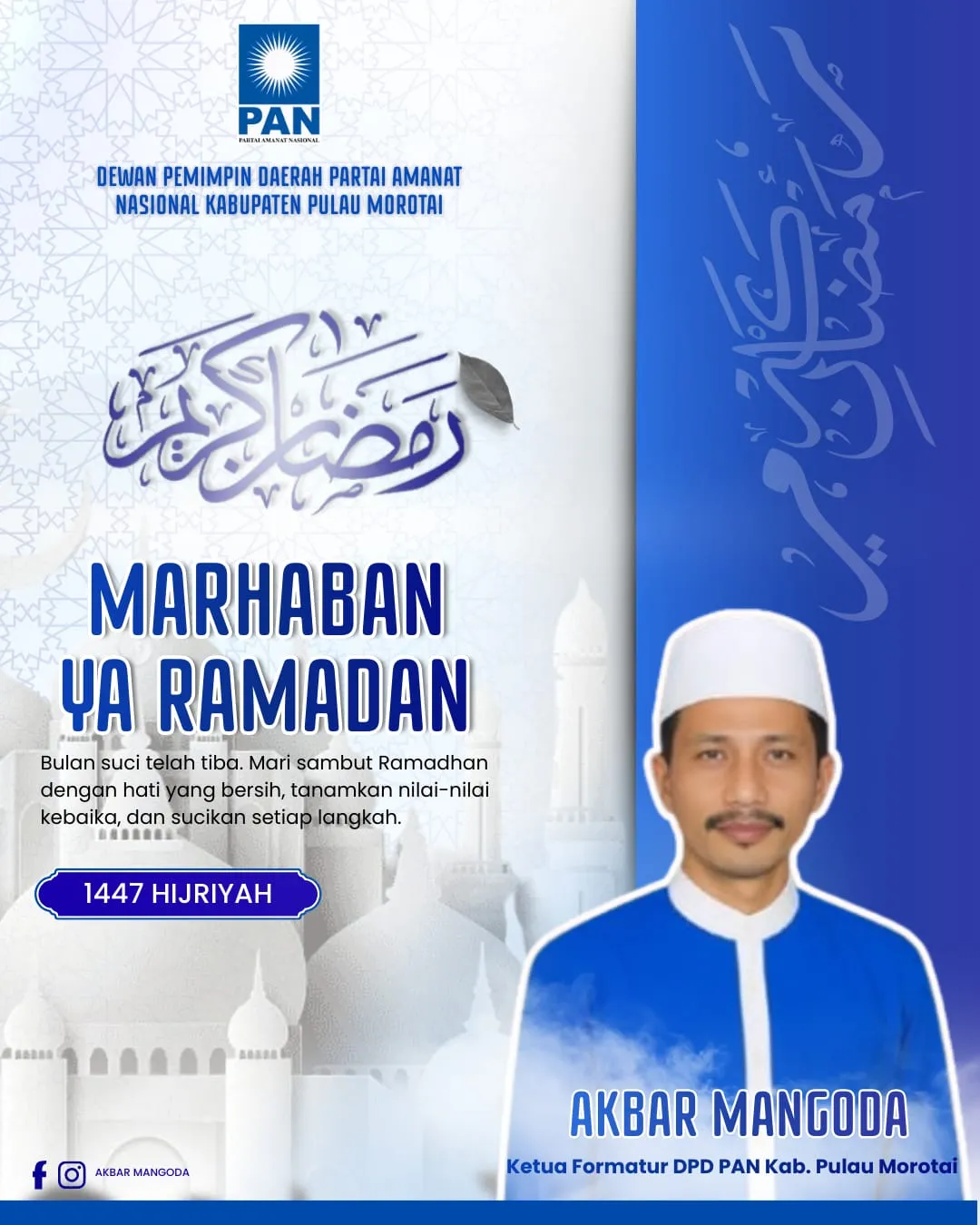



























Saat ini belum ada komentar